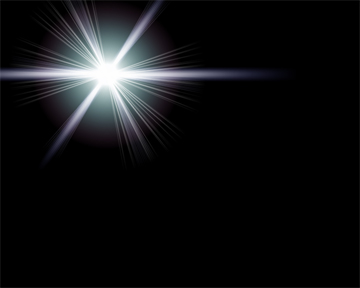 Kita ini adalah cahaya.
Kita ini adalah cahaya.Tulisan ini masih nyambung dengan posting-an sebelumnya yang berjudul Black LitNation. Di tulisan sebelumnya itu, saya membahas arti kata black menurut wacana sosio-historis, yang ternyata kata tersebut dekat dengan makna kebodohan/kemunduran. Oleh karenanya, saya menghimbau kepada Djarum Black untuk membuktikan diri bahwa mereka jauh dari kesan black yang seperti itu. Tentu tidak cukup dengan mengadakan Black Innovation Award. Makanya saya mengusulkan adanya sebuah gerakan Black LitNation.
Masih seputar kata black, namun kini kita akan mengkajinya dari sisi filosofis. Seperti yang telah didiskusikan, kata black mengandung sifat dark. Hitam itu gelap dan gelap itu hitam. Bicara tentang gelap, dari sudut pandang filsafat, ini masih ada kaitannya dengan konsep “ketiadaan”.
Aliran Neoplatonisme termasuk ke dalam golongan filsafat dualisme. Ia membagi manusia ke dalam dua struktur yang membangunnya; jiwa (ruh) dan raga (badan). Menurut sumber aslinya, Plato, asalnya ruh itu dari dunia Ide. Adapun menurut anak-anak didiknya, Neoplatonis, asalnya ruh itu dari Sang Sumber Cahaya.
Sebagaimana manusia, alam dunia inipun terbagi ke dalam dua bagian; kutub cahaya dan kutub kegelapan. Sebagaimana kita ketahui, cahaya itu memiliki radius pancaran yang terbatas. Kegelapan itu bermakna “tidak tersentuh cahaya” atau dengan kata lain “ketiadaan cahaya”. Manusia tercipta dari percikan cahayanya Sang Sumber Cahaya, kemudian terperangkap dalam raga di alam kegelapan. Oleh karena itu, sejatinya kita ini adalah cahaya itu sendiri.
Dikarenakan di dalam diri kita ini terbangun dari unsur cahaya. Maka manusia sangat mungkin untuk menyatukan dirinya bergabung kembali ke Sang Sumber Cahaya. Ibarat kita melihat api unggun. Agar kita dapat melihat ke sekeliling dengan terang, merasakan kehangatan pancarannya, tentu konyol jika kita mengharapkan api unggun yang mendatangi kita. Justru kitalah yang harus menyambanginya.
Adanya pemahaman bahwa manusia bisa bersatu kembali dengan Dzat asalnya inilah yang banyak mengilhami pemikiran-pemikiran aliran tasawuf dalam perkembangan keagamaan Islam. Paham wihdatul wujud (bersatunya wujud), atau dalam basanya jawanya; manunggaling gusti, menyatakan bahwa manusia dapat bersatu dengan diri Allah, melalui usaha-usaha tertentu yang bertingkat-tingkat (baca : dzikir dan gaya hidup). Saat itu tercapai, maka inilah yang disebut dengan “Allah adalah saya dan saya adalah Allah”.
Pemahaman teologi yang “mutakhir” ini tentu saja tidak mudah diterima oleh logis-rasional keimanan Islam dan juga oleh pemahaman umum umat muslim. Oleh karenanya, dalam perjalanan sejarahnya banyak tokoh tasawuf yang dihukum mati oleh otoritas setempat karena dianggap menyesatkan. Sebut saja tokoh sufi Al-Hallaj dan di Indonesia ada Hamzah Fansuri atau Syekh Siti Jenar.
Di jalur pendidikan, secara elegan Al-Ghazali meng-counter pemahaman-pemahaman filsafat yang dinilai merusak sendi-sendi Islam melalui penerbitan bukunya yang berjudul Talafuth Al-falasifah (Kesalahan-kesalahan Filsafat).
Terlepas dari itu semua, kita dapat memetik satu pelajaran penting dari filsafatnya Neoplatonis. Menjadi gelap ternyata ialah suatu fase yang niscaya akan dijalani seorang manusia. Seorang manusia tidak mungkin mencapai eksistensinya yang sejati tanpa melalui kegelapan ini. Adapun makna eksistensi itu dapat berarti macam-macam; kebenaran universal tentang dunia menurut Socrates, menjadi hamba yang sholeh menurut agama, mencapai aktualisasi diri menurut Psikologi Humanisme, meraih ambisi sesuai dengan keinginan menurut para ahli bisnis dan lain-lain. Kita ini semua “bukan apa-apa” (gelap) pada mulanya, diri kita sendirilah yang mengubah kita menjadi “apa-apa” (bercahaya).
Permasalahannya ialah sejauh mana usaha kita untuk melintasi kegelapan yang sekarang sedang kita alami ini ? Sudahkah kita memanfaatkan hati nurani dan akal pikiran seoptimal mungkin ? Sejauh mana posisi kita dari titik cahaya ? Apakah kita hanya akan duduk nongkrong dan menikmati titik cahaya nun jauh di sana ? Atau bersusah payah untuk mendekatinya ?
No comments:
Post a Comment